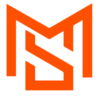Oleh M. Sodikin, S.T.
Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, ancaman sering kali menjadi alat yang dianggap ampuh untuk menciptakan ketertiban. Negara memakai hukum pidana untuk mencegah kriminalitas, aparat memakai kekuasaan untuk mengendalikan konflik, bahkan dalam budaya populer, orang tua, guru, dan pemimpin komunitas masih terbiasa menggunakan kalimat-kalimat bernada intimidatif: “Awas kalau melanggar,” “Jangan macam-macam, nanti dihukum.” Narasi-narasi seperti ini membentuk logika umum bahwa manusia hanya akan taat jika ada ketakutan, hanya akan mengikuti aturan jika merasa terancam. Namun, apakah memang kita harus diancam agar patuh? Apakah peradaban manusia dibangun di atas rasa takut, bukan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab?
Dalam konteks politik, ancaman sering digunakan oleh rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam sejarah kita, masa Orde Baru menorehkan contoh bagaimana ketakutan terhadap negara membuat masyarakat bungkam, tidak bersuara, dan menerima segalanya dalam diam. Memori tentang operasi militer, penculikan aktivis, dan pembungkaman pers menjadi luka sosial yang menandakan bahwa kepatuhan yang lahir dari ketakutan bukanlah ketaatan yang sehat, melainkan bentuk tekanan sistemik terhadap kebebasan sipil. Dalam demokrasi, semestinya ketaatan warga negara bukan dilandaskan pada ketakutan terhadap negara, melainkan pada kesadaran akan tanggung jawab bersama. Jika rakyat mengikuti aturan hanya karena takut ditangkap, maka negara telah gagal mendidik warganya menjadi manusia merdeka yang memiliki integritas.
Secara sosial, pendekatan yang menekankan ancaman menciptakan relasi kuasa yang timpang. Masyarakat yang dibentuk dengan narasi takut cenderung pasif, tidak kritis, dan apatis. Budaya seperti ini mudah sekali terjebak dalam patronase, di mana rakyat hanya manut pada elit karena takut kehilangan akses atau dihukum. Dalam jangka panjang, ini menghasilkan masyarakat yang permisif terhadap ketidakadilan, karena takut bersuara. Padahal kekuatan sosial terletak pada keberanian warga untuk menyuarakan kebenaran, mempertanyakan kebijakan, dan terlibat aktif dalam perubahan. Sebuah masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang diam karena takut, tetapi masyarakat yang hidup karena sadar dan peduli.
Dari sudut budaya, penggunaan ancaman terus-menerus dapat melahirkan masyarakat yang trauma, penuh kepura-puraan, dan rendah rasa percaya diri. Dalam banyak komunitas, orang berpura-pura sopan atau patuh hanya karena takut pada hukuman sosial. Mereka memakai topeng untuk diterima, bukan menunjukkan siapa dirinya secara jujur. Budaya semacam ini tidak memerdekakan individu, tetapi justru menciptakan tekanan mental dan memperpanjang siklus ketidakotentikan. Ketika ancaman menjadi norma budaya, kita kehilangan ruang untuk diskusi terbuka, untuk bertumbuh dalam perbedaan, dan untuk menemukan jati diri secara sehat. Ancaman melahirkan keseragaman yang palsu, bukan kebersamaan yang otentik.
Dalam ajaran agama pun, pendekatan ancaman bukanlah inti ajaran. Islam, misalnya, tidak dibangun atas dasar ketakutan semata. Al-Qur’an sendiri sangat sering menyebutkan kasih sayang Allah lebih dari azab-Nya. Nabi Muhammad SAW pun diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai pembawa teror. Sabdanya yang terkenal, “Yassiruu wa laa tu’assiruu, basysyiruu wa laa tunaffiruu”—“Permudahlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari,” adalah landasan spiritual sekaligus sosial budaya yang sangat relevan untuk zaman ini. Dalam politik, ini berarti pemimpin harus hadir untuk memudahkan urusan rakyat, bukan memperumitnya. Dalam sosial budaya, ini berarti masyarakat harus saling mendorong dalam kebaikan, bukan saling menakut-nakuti.
Oleh karena itu, membangun peradaban dengan pendekatan ancaman bukan hanya usang, tetapi juga keliru secara prinsip. Kita hidup di zaman yang menuntut kebebasan berpikir, kolaborasi sosial, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan. Semua ini tidak akan tumbuh dalam budaya ketakutan. Kita butuh ruang yang aman untuk berbicara, belajar, dan berbeda pendapat. Kita butuh pemimpin yang menginspirasi, bukan mengintimidasi. Kita butuh masyarakat yang saling mempercayai, bukan saling mencurigai. Dan semua itu hanya bisa dicapai jika kita meninggalkan pendekatan ancaman, lalu menggantinya dengan pendekatan kesadaran, kasih, dan tanggung jawab bersama.
Kita ditugaskan bukan untuk mempersulit manusia, tetapi untuk mempermudah. Bukan untuk menakut-nakuti sesama, tetapi untuk memberi harapan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, ketaatan yang lahir dari cinta dan kesadaran akan jauh lebih kuat daripada kepatuhan yang lahir dari rasa takut. Maka pertanyaannya kini berubah: beranikah kita membangun masyarakat tanpa ancaman? Kalau jawabannya ya, maka di situlah awal mula lahirnya manusia merdeka, bangsa yang berdaulat, dan budaya yang membebaskan.
-ms-